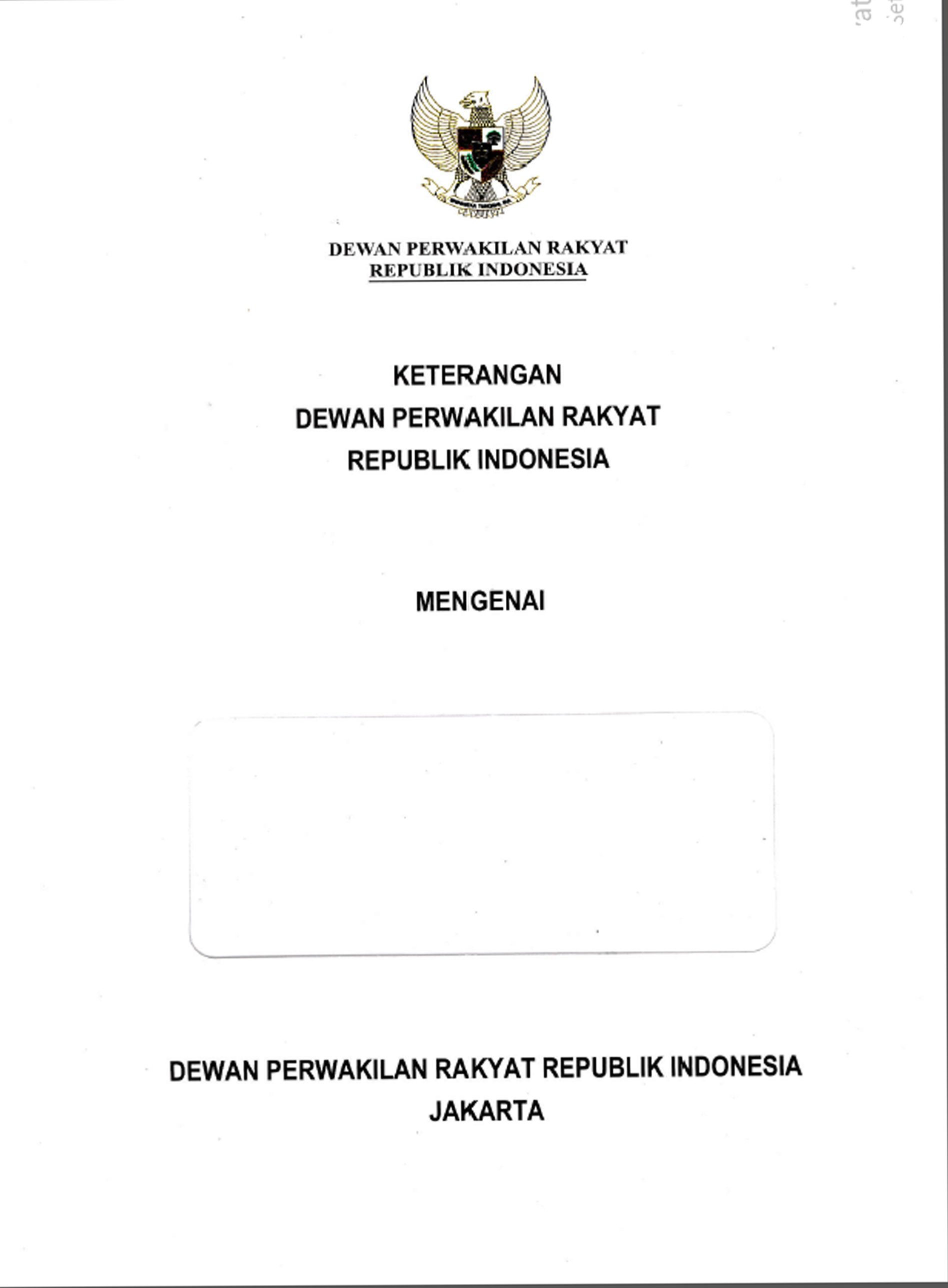Sistem Pemberian Keterangan DPR (SITERANG)
65/PUU-XIX/2021
Kerugian Konstitusional: Bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat kekakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU 5/1960) yang tidak sesuai dengan transaksi-transaksi atas tanah yang ada di masyarakat Indonesia termasuk dalam transaksi perbankan syariah. Selain itu kerugian konstitusional tersebut juga disebabkan oleh UU 21/2008 yang mengatur secara tidak jelas dimana Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008 memberikan delegasi blangko kepada MUI (non Lembaga Negara) maupun BI/OJK (Lembaga Negara) sehingga terjadi disharmoni pengaturan perbankan syariah yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 21/2008 juga bersifat multi tafsir karena memberikan delegasi kewenangan kepada 2 (dua) lembaga yang berbeda, yakni MUI dengan BI/OJK, dengan kewenangan pembentukan hukum yang berbeda juga. Hal ini menimbulkan kebingungan Pemohon dan berpotensi menimbulkan kerugian potensial dan actual berupa keraguan apakah transaksi perbankan syariah telah memiliki kepastian hukum yang memberikan keadilan bagi Pemohon. Dilema ini menurut Pemohon merupakan kondisi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan konstitusi (vide Perbaikan Permohonan Hlm 5-8). Legal Standing: 1. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Bahwa Pemohon menyatakan mendapatkan kepastian hukum yang adil dan memberikan manfaat dan kemudahan yang sama untuk mengakses layanan perbankan syariah berdasarkan prinsip negara hukum adalah hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh konstitusi berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 (vide perbaikan permohonan hal. 4) Bahwa terkait batu uji yang digunakan oleh Pemohon terlebih dahulu DPR menerangkan sebagai berikut: - Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak konstitusional Pemohon melainkan pada intinya mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga ketentuan ini tidak tepat apabila dianggap sebagai dasar adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi Pemohon. - Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dimana pengaturan pasal a quo telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama terhadap seluruh pengguna layanan perbankan syariah. Selain itu, dalam transaksi-transaksi di perbankan syariah sudah semestinya dijalankan berdasarkan prinsip syariah. - Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, namun sebelum menggunakan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ini sebagai batu uji, Pemohon seharusnya terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) tersebut. Bahwa naskah komprehensif perubahan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “kemudahan dan perlakuan khusus” muncul sebagai bentuk dari perluasan pasal-pasal Hak Asasi Manusia. Hak kemudahan dan perlakuan khusus sama dengan “affirmative action” merupakan apa yang disebut “the special treatment” yang berasal dari ide dasar “treat like cases alike atau different cases differently”. Pengaruh affirmative action menunjukkan prinsip yang tidak hanya berakar dari aktivitas, melainkan juga tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Hal ini sesuai dengan pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan: Sekalipun norma konstitusi dimaksud memberikan kesempatan bagi setiap orang, namun bukan bermakna bahwa norma tersebut berlaku untuk siapa pun. Sebab, frasa “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 harus dibaca dalam satu napas dengan frasa “guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan membaca dua frasa “guna mencapai persamaan dan keadilan” tersebut dalam satu kesatuan maksud, maka kemudahan dan perlakuan khusus dimaksud hanya boleh atau dapat diberikan kepada orang yang apabila tanpa adanya kemudahan dan perlakuan khusus dimaksud ia tidak mampu mencapai persamaan dengan orang lain, sehingga ia tidak akan mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 merupakan hak yang diberikan secara khusus kepada orang yang memiliki hambatan tertentu dalam mencapai persamaannya dengan orang lain, sehingga membutuhkan apa yang dikenal dengan affirmative action. Penegasan Mahkamah Konstitusi perihal keterkaitan affirmative action sebagai wujud pelaksanaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dapat dibaca, misalnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, tanggal 23 Desember 2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008, tanggal 12 Maret 2014; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013, tanggal 12 Maret 2014. Tidak hanya itu, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara substansial menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara (affirmative actions) ditujukan untuk mendorong dan sekaligus mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Ditegaskan pula dalam putusan-putusan tersebut, affirmative action dalam pemilu sebagai wujud dari pelaksanaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 misalnya kuota 30 (tiga puluh) persen bagi perempuan sebagai bentuk perlakuan khusus untuk mencapai kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian menjadi tidak relevan apabila Pemohon mendasarkan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pada ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena Pemohon tidak termasuk dalam kategori orang yang memerlukan perlakuan khusus sehingga tidak memerlukan adanya affirmative action. - Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Hak kepemilikan tersebut tidak memiliki korelasi dengan pasal a quo yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon yang mana mengatur mengenai definisi prinsip syariah, kegiatan usaha perbankan syariah yang wajib tunduk pada prinsip syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon sama sekali tidak mengancam atau merampas hak milik pribadi Pemohon. Oleh karenanya menjadi tidak relevan apabila Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dijadikan dasar adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dalam pengujian pasal a quo. - Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Telah sangat jelas bahwa ketentuan a quo tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara melainkan amanat bagi penyelenggara negara untuk menjamin, mengatur, dan menuangkan pelaksanaan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan agar hak asasi manusia tersebut dapat ditegakkan dan dilindungi. Dengan demikian, jelas bahwa tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya pasal a quo UU 21/2008, selain itu pasal a quo UU 21/2008 juga tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diuraikan oleh Pemohon. 2. Terkait hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji Bahwa Pemohon menguraikan kerugian konstitusional disebabkan oleh Pasal 1 angka 12, dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008 memberikan delegasi blangko kepada MUI maupun BI/OJK sehingga terjadi disharmoni pengaturan perbankan syariah yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Terhadap uraian Pemohon tersebut, DPR menerangkan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon telah dipenuhi dengan adanya pengaturan dalam pasal-pasal a quo UU 21/2008. Ketentuan Pasal 1 angka 12 UU 21/2008 telah menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip syariah dalam perbankan syariah, dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 21/2008 telah sangat jelas mengatur kegiatan usaha apa saja yang wajib tunduk kepada prinsip syariah yang difatwakan oleh MUI yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia, atau yang saat ini kewenangan tersebut telah dialihkan dan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 21/2011). Dalam perbaikan permohonannya, Pemohon mendalilkan dasar kerugiannya adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU 5/1960) yang tidak sesuai dengan transaksi-transaksi atas tanah yang ada di masyarakat Indonesia termasuk dalam transaksi perbankan syariah. Namun dalam permohonan tersebut, Pemohon hanya mengajukan pengujian ketentuan UU 21/2008 dan tidak mengajukan pengujian UU 5/1960 sehingga menjadi tidak jelas apa yang sebenarnya menjadi dasar kerugian yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, DPR menekankan bahwa permasalahan yang dialami dan disampaikan oleh Pemohon tidak jelas dan membingungkan yang diakibatkan oleh ketidakjelasan uraian materi yang disampaikan oleh Pemohon dalam perbaikan permohonannya dan ketidaksesuaian antara posita dengan petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sehingga permohonan Pemohon ini harus dinyatakan obscuur libel. 3. Terkait adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa Pemohon mendalilkan pengaturan perbankan syariah bersifat tidak jelas menimbulkan kebingungan Pemohon dan berpotensi menimbulkan kerugian potensial dan actual berupa keraguan apakah transaksi perbankan syariah telah memiliki kepastian hukum yang memberikan keadilan bagi Pemohon. Dilema ini menurut Pemohon merupakan kondisi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan konstitusi. DPR berpandangan bahwa kebingungan Pemohon bukanlah suatu kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Jika pemohon ingin lebih memahami lebih lanjut mengenai prinsip syariah dalam sistem perbankan syariah maka Pemohon dapat meminta informasi kepada OJK. Kepahaman Pemohon terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah suatu keharusan mengingat Pemohon adalah seorang advokat yang bekerja memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat khususnya dalam membela masyarakat dengan menggunakan jasanya. Permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat tentunya cukup komplek dan tidak hanya sekedar pidana dan perdata, sehingga merupakan suatu kelaziman dan keharusan bagi Pemohon untuk memahami peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku khususnya di Indonesia. Dengan demikian, Pemohon telah jelas tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik aktual maupun potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi atas berlakunya pasal a quo UU 21/2008. 4. Terkait adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada angka 1, 2, dan 3 di atas, Pemohon yang mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dilanggar oleh keberlakuan ketentuan pasal a quo tidaklah relevan karena Pemohon tidak jelas dalam menyampaikan uraian permasalahannya. Jika Pemohon merasa kurang paham mengenai rumusan ketentuan pasal a quo, hal tersebut tidak serta merta menjadikan suatu ketentuan dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara. Ketidakpahaman tersebut dapat diatasi dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, mendatangi lembaga atau orang yang kompeten dan memahami pengaturan terkait perbankan syariah dan hal-hal terkait dengan perbankan syariah dan bukan malah mengajukan pengujian ketentuan a quo ke Mahkamah Konstitusi dan memohon agar ketentuan a quo dimaknai sebagaimana pemahaman Pemohon yang jelas keliru. Oleh karenanya, tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan pasal a quo. 5. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa Pemohon mendalilkan jika Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 21/2008 diberikan penafsiran yang jelas maka Pemohon akan dapat kembali mengajukan fasilitas layanan perbankan syariah seperti sedia kala. Terhadap dalil tersebut DPR menerangkan bahwa pengaturan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dan dianggap merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut telah ada sejak diundangkannya UU 21/2008 pada tahun 2008 dan berlaku hingga saat ini. Selain itu, penafsiran yang jelas yang dimaksud oleh Pemohon ini harus dilihat kembali, jangan sampai pengaturan yang diubah sebagaimana “jelas” dalam perspektif Pemohon tersebut justru menimbulkan permasalahan hukum baru bagi masyarakat Indonesia yang justru menjadikan UU 21/2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1, 2, 3, dan 4, maka sudah dapat dipastikan dengan dikabulkan atau tidak permohonan pengujian ketentuan Pasal-Pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. Dengan demikian, menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konsitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan: a. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 21/2008 juga bersifat multi tafsir karena memberikan delegasi kewenangan kepada 2 lembaga yang berbeda, yakni MUI dengan BI/OJK, dengan kewenangan pembentukan hukum yang berbeda juga (vide Perbaikan Permohonan hlm 6) Bahwa terkait dengan pendelegasian kewenangan pengaturan prinsip syariah melalui fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, DPR menerangkan sebagai berikut: 1) Bahwa fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diakses dari laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah dengan kata lain yaitu nasihat orang alim. 2) Bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius yang meletakkan agama sebagai panduan hidup berbangsa dan bernegara. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia telah mengakar kuat dalam berbagai bidang kehidupan. Terbentuknya berbagai organisasi Islam di Indonesia terikat kuat dengan sosiologi beragama masyarakat. MUI di kalangan akademisi didefinisikan sebagai organisasi semi-pemerintah di Indonesia yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan saran dan fatwa tentang agama dan masalah bangsa kepada pemerintah dan masyarakat. Selain itu, MUI juga diharapkan turut mempromosikan persatuan di antara umat Islam, dan bertindak sebagai mediator antara pemerintah dan ulama. 3) Bahwa yang dimaksud dengan MUI menurut Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (Perpres 151/2014) adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. 4) Bahwa fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (fuqaha) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’ maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam. 5) Bahwa dalam praktik, doktrin (pendapat ahli hukum) banyak mempengaruhi pelaksanaan administrasi Negara, demikian juga dalam proses pengadilan. Seorang hakim diperkenankan menggunakan pendapat ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, kemudian bagi seorang pengacara/pembela yang sedang melakukan pembelaannya pada suatu perkara perdata, seringkali mengutip pendapat-pendapat ahli sebagai penguat pembelaannya. Begitu pula dengan fatwa, dalam sejarah Peradilan Agama di Indonesia, Pengadilan Agama untuk dapat memeriksa, menangani, dan memutus perkara perdata (masalah kekeluargaan, kewarisan, perceraian, dan lain sebagainya), maka Pengadilan Agama memakai fatwa sebagai landasan hukum, yakni fatwa disepakati oleh Mahkamah Agung bersama Pengadilan Agama. Pada dasarnya, fatwa hanyalah pendapat, nasehat ulama yang tidak mengikat, dan untuk dapat berlaku mengikat maka fatwa harus melewati legislasi terlebih dahulu yang kemudian menjadi peraturan perundang-undangan. 6) Bahwa UU 21/2008 memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa terkait suatu hukum atas suatu akad yang menjadi dasar adanya produk dan jasa perbankan syariah. Kemudian fatwa dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang telah dialihkan dan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU 21/2011 dan peraturan pelaksanannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini merupakan pengakuan bahwa MUI merupakan lembaga yang berwenang untuk menerbitkan fatwa yang dijadikan dasar dalam kegiatan usaha perbankan syariah. 7) Bahwa frasa “prinsip Syariah” yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah a quo sebagai “prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah”, yang kemudian diperkuat dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU a quo bahwa prinsip Syariah yang dimaksudkan difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, secara jelas memberikan batasan bahwa fatwa yang digunakan dan dijadikan rujukan dalam kegiatan perbankan Syariah adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), bukan dari lembaga atau organisasi kemasyarakatan atau keagamaan lainnya. Selain itu, asas kepastian hukum juga melatarbelakangi Pembentuk Undang-Undang memberikan kewenangan mengeluarkan fatwa kepada MUI sebagai majelis yang beranggotakan para ulama yang merepresentasi pelbagai kalangan. 8) Bahwa pembentuk Undang-Undang memahami bahwa fatwa tidak termasuk dalam jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan dan Majelis Ulama Indonesia bukan pula merupakan lembaga yang memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019), sehingga agar fatwa ini dapat diaplikasikan dan kegiatan perbankan Syariah, pembentuk Undang-Undang memerintahkan lembaga yang memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yakni Bank Indonesia (dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan perkembangan legislasi di bidang perbankan) untuk mengadopsi fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI yang dalam hal ini dikeluarkan oleh organ Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) agar dapat menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berlaku secara umum dan luas. Sebagai sebuah nilai yang diyakini oleh umat Islam di negeri ini, fatwa mempunyai kedudukan penting dalam penyusunan setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur umat muslim terkait dengan prinsip Syariah Islam. Karena setiap penyusunan peraturan perundangan sudah seharusnya menyerap dan mengakomodasi nilai-nilai yang telah berkembang dan diyakini oleh masyarakat. 9) Apabila Pemohon menghendaki fatwa dikeluarkan oleh BI/OJK, maka hal ini justru akan menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat mengingat bahwa BI/OJK tidak memiliki kompetensi menilai dan memahami hukum islam sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama. Dengan demikian, telah jelas bahwa pengaturan kewenangan kelembagaan sebagaimana yang terdapat dalam pasal a quo termasuk kewenanganannya dalam hal perbankan syariah telah memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha keuangan syariah dan masyarakat. b. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008 telah memberikan delegasi blangko kepada MUI (non Lembaga Negara) maupun BI/OJK (Lembaga Negara) sehingga terjadi disharmoni pengaturan perbankan syariah yang menyebabkan ketidakpastian hukum (vide Perbaikan Permohonan Hlm 5-6). 1) Terhadap dalil tersebut DPR menerangkan dalam pendelegasian kewenangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) diatur sebagai berikut: 198. Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah. 200. Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas: a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan b. jenis Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan lampiran 198 dan 200 tersebut, maka pembentuk undang-undang jika akan mendelegasikan suatu ketentuan atau aturan maka harus ada persyaratan yang jelas mengenai materi muatan yang akan didelegasikan dan jenis didelegasikan kepada jenis aturannya, jika tidak memenuhi aturan tersebut itulah yang disebut delegasi blangko. 2) Bahwa terkait dengan delegasi blangko, larangan penggunaan delegasi blangko terdapat di dalam UU 12/2011. Dalam Pedoman Nomor 210 Lampiran UU 12/2011, melarang adanya delegasi blangko yang diatur sebagai berikut: 210. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko. Contoh 1: Pasal … Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Contoh 2: Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang pengaturan pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati. 3) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas delegasi blangko seperti apa yang dimaksud oleh Pemohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) UU 21/2008 pembentuk undang-undang telah jelas memberikan kewenangan secara atribusi kepada MUI untuk memberikan fatwa mengenai prinsip syariah dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah lainnya. Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU 21/2008 memberikan pengaturan bahwa fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI harus dikuatkan melalui pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Peraturan Bank Indonesia. Selanjutnya, UU a quo telah jelas mengatur mengenai ruang lingkup materi muatan dan ketentuan-ketentuan yang diberikan delegasi oleh pembentuk undang-undang kepada MUI maupun kepada BI/OJK. Sehingga dalam hal ini Pemohon perlu memperjelas delegasi blangko yang bagaimana yang dimaksud oleh Pemohon dalam pasal a quo. c. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon banyak menguraikan teori-teori mengenai hak milik atas tanah dan perkembangan yang ada terkait dengan hak-hak yang muncul atas tanah dan permasalahannya dalam perspektif Pemohon, serta uraian mengenai hak-hak kebendaan. Tetapi Pemohon sama sekali tidak memberikan dasar uraian Permohonan yang jelas atas pertautan pengaturan dalam UU 21/2008 dengan kerugian Pemohon, sehingga apa yang tengah dipermasalahkan oleh Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas mengingat Pemohon banyak menguraikan mengenai UU 5/1960 yang tidak dimohonkan pengujiannya dalam Permohonan Pemohon. d. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan pengujian yang serupa dengan permasalahan yang terdapat dalam permohonan a quo, yakni dalam perkara Nomor 12/PUU-XIX/2021 yang mempermasalahkan UU 5/1960 dikaitkan dengan UU 21/2008, yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Adapun pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi terhadap perkara tersebut adalah sebagai berikut: • [3.13.1] ...mengingat pentingnya kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah, in casu hak milik, maka setiap perbuatan hukum yang menyangkut peralihan atau pembebanannya menjadi tidak sah jika tidak dilakukan pendaftaran pada instansi yang berwenang untuk itu. Hal ini bukanlah merupakan bentuk penafsiran atau pemahaman secara letterlijk terhadap norma Pasal 23 UUPA sebagaimana dalil Pemohon tetapi merupakan suatu keharusan yang mesti dilewati sesuai dengan proses dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan demi memperoleh kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah tersebut. Sementara, kuitansi yang didalilkan oleh Pemohon sudah cukup menjadi bukti kepemilikan adalah tidak tepat karena pada hakikatnya kuitansi hanyalah merupakan bukti pembayaran atau transaksi, bahkan akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT pun belum dapat disebut sebagai bukti kepemilikan tetapi baru sebagai salah satu syarat adanya peralihan hak. Oleh karena itu, berkaitan dengan bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah (vide Pasal 3 huruf a, Pasal 4 ayat (1) PP 24/1997), karena melalui pendaftaran tanah dimaksud akan dapat diketahui tentang siapa sesungguhnya pemegang hak atas tanah, kapan diperalihkannya hak atas tanah tersebut serta siapa pemegang hak yang baru termasuk juga jika tanah tersebut dibebani hak tanggungan. Dalam kaitan ini jika kuitansi saja yang dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dalil Pemohon maka hal tersebut justru dapat mengaburkan esensi kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah, yang pada akhirnya justru merugikan perbankan/kreditor, in casu perbankan syariah sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau kredit. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan proses dan prosedur peralihan serta pendaftaran hak atas tanah yang memerlukan waktu lama dan berbiaya mahal karena dibutuhkan beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, jika tidak dikecualikan untuk perbankan syariah adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. • [3.13.2] Bahwa selanjutnya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap UU 21/2008 berkenaan dengan hak kebendaan dalam transaksi perbankan syariah. Permintaan Pemohon ini bukan merupakan objek permohonan Pemohon (objectum litis) yang dinyatakan baik dalam perihal permohonan dan kewenangan Mahkamah. Sementara, dalam menguraikan kerugian konstitusional Pemohon hanya disinggung sekilas tentang keberadaan UU a quo namun tidak menguraikan apa sesungguhnya hak konstitusional Pemohon yang menurut anggapan Pemohon dirugikan dengan berlakunya UU a quo. Terlebih-lebih dalam uraian alasan permohonan (posita), Pemohon tidak menjelaskan pertentangan norma UU 21/2008 dengan UUD 1945 sehingga Mahkamah sulit untuk memahami apa sesungguhnya yang dipersoalkan oleh Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma UU 21/2008 sehingga dalil Pemohon a quo tidak relevan untuk dipertimbangkan. e. Bahwa berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang diuraikan oleh Pemohon dalam perkara ini merupakan suatu permasalahan yang memiliki kemiripan dengan permasalahan yang diajukan oleh Pemohon sebelumnya dalam perkara Nomor 12/PUU-XIX/2021 dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya tidak relevan apabila dikaitkan dengan kewenangan MUI dan BI/OJK dalam pasal a quo termasuk dengan definisi prinsip syariah dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU 21/2008. f. Bahwa produk-produk seperti mudharabah, musyarakah dan lainnya tidak diatur secara rinci di dalam UU 21/2008, karena secara teknis produk tersebut mengikuti sesuai dengan perkembangan kegiatan bisnis perbankan syariah. Kemudian terkait dengan hak kebendaan, telah adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang didalam pengaturan kedua undang-undang tersebut tidak ditemukan pertentangan dengan syariat islam sehingga dipandang tidak perlu ada pengaturan kembali terkait hak kebendaan dalam UU 21/2008. Apabila terdapat pengaturan mengenai hak kebendaan dalam UU 21/2008, justru hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum. g. Bahwa dalam Petitum Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi untuk “Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah (Lembar Negara Nomor 94 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867) khususnya mengenai hak kebendaan dalam transaksi perbankan syariah atau melakukan pembentukan undang-undang yang di dalamnya mengatur mengenai hak kebendaan dalam transaksi perbankan Syariah”, DPR memandang permohonan ini merupakan permohonan yang tidak jelas mengingat Pemohon tidak mencantumkan ketentuan mana yang harus diubah. Selain itu Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator seharusnya hanya dapat membatalkan dan mempertegas undang-undang yang diujikan, sedangkan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mempertegas atau membatalkan undang-undang seharusnya dilaksanakan oleh pembentuk Undang-Undang, hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU 12/2011. Petitum ini pun juga dituliskan oleh Pemohon dalam pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon melalui Perkara Nomor 12/PUU-XIX/2021 yang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ditanggapi sebaagi berikut: “[3.13.2] Bahwa selanjutnya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap UU 21/2008 berkenaan dengan hak kebendaan dalam transaksi perbankan syariah. Permintaan Pemohon ini bukan merupakan objek permohonan Pemohon (objectum litis) yang dinyatakan baik dalam perihal permohonan dan kewenangan Mahkamah. ….” Maka menjadi tidak relevan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
65/PUU-XIX/2021
Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 21/2008
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945