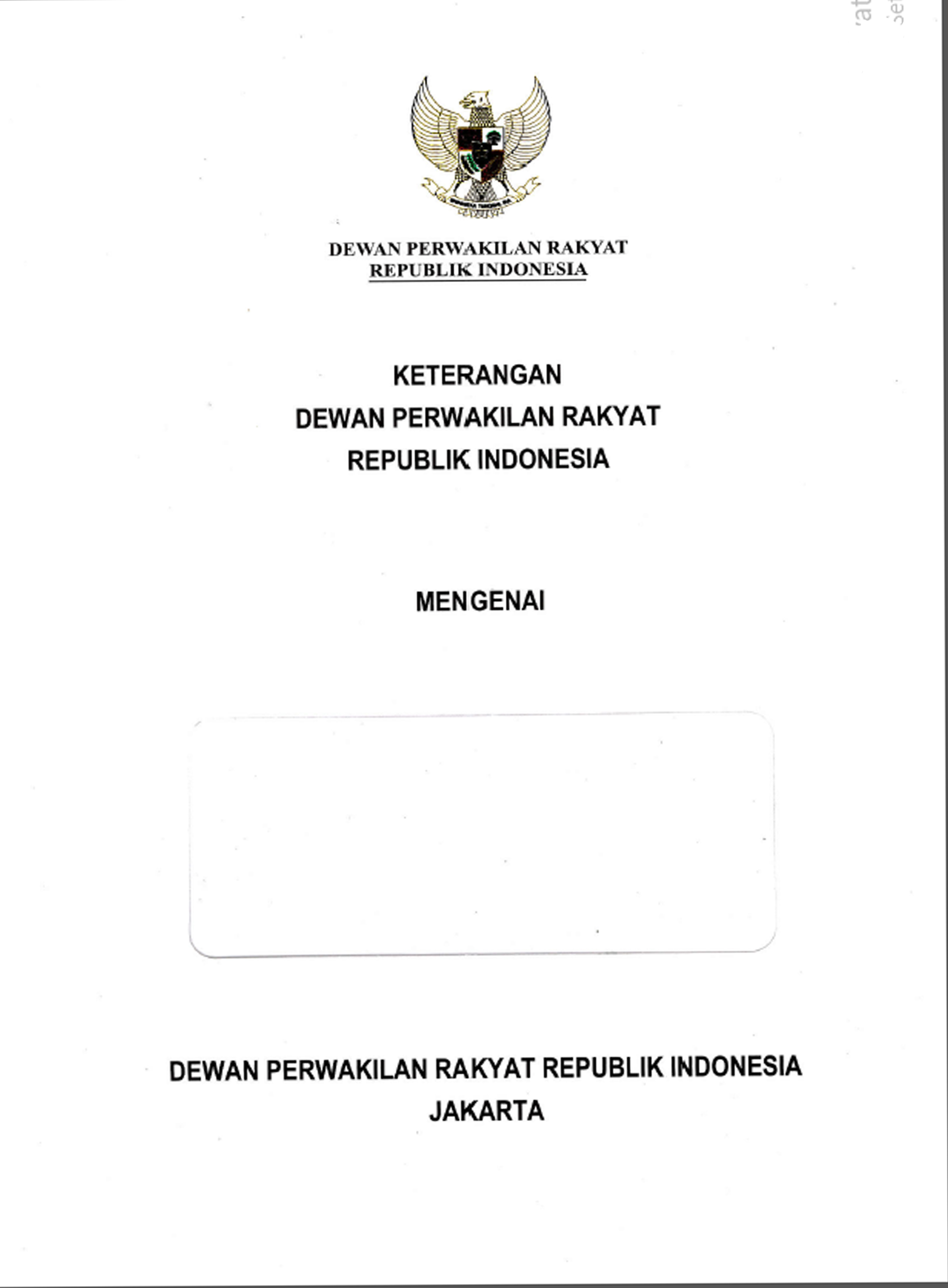Sistem Pemberian Keterangan DPR (SITERANG)
16/PUU-XIX/2021
Kerugian konstitusional: Bahwa Para Pemohon merasa ketentuan Pasal a quo menyebabkan beban kerja yang sangat berat dan tidak rasional bagi Para Pemohon selaku petugas penyelenggara Pemilu pada tahun 2019 karena pemilu yang diselenggarakan secara serentak dalam format lima jenis surat suara dalam waktu yang bersamaan yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (vide Perbaikan Permohonan Hlm 4 Nomor 7 dan Hlm 6 Nomor 17). Legal standing: 1. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan Halaman 5 angka 12-14). Terhadap dalil tersebut DPR menerangkan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan konstitusi, yang merepresentasikan bahwa Republik Indonesia menerapkan sistem politik demokrasi. Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 tidak relevan untuk dijadikan batu uji dalam permohonan pengujian a quo karena tidak mengandung ketentuan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara. Bahwa ketentuan Pasal a quo tidak menghalangi Para Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena Para Pemohon tidak memberikan argumentasi dalam hal apa ketentuan Pasal a quo menghalangi Para Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Begitu pun halnya dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji karena Para Pemohon tidak memberikan dasar argumentasi yang jelas dalam hal apa ketentuan Pasal a quo UU Pemilu menghalangi Para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya mengingat ketentuan Pasal a quo tidak mengatur adanya pembatasan tertentu atas pelaksanaan hak konstitusional tersebut. 2. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang Bahwa Para Pemohon pada intinya merasa dirugikan terhadap ketentuan Pasal a quo karena konsekuensi dari pengaturan Pasal a quo UU Pemilu menyebabkan tugas dan beban kerja yang berat terhadap teknis penyelenggaraan pemilu. Terhadap dalil kerugian tersebut DPR memandang bahwa Para Pemohon yang berpartisipasi secara sadar dan sukarela sebagai penyelenggara pemilu karena telah menyatakan sumpah/janji anggota PPK, PPS dan KPPS yang sudah semestinya Para Pemohon memiliki beban kerja yang sepatutnya dipahami oleh Para Pemohon sebagai konsekuensi atas jabatan yang diembannya. Oleh karena itu kerugian yang didalilkan Para Pemohon sudah jelas tidak disebabkan oleh berlakunya ketentuan Pasal a quo. 3. Terkait adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin nomor 2, tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal a quo sehingga tidak ada kerugian konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual maupun potensial menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan diberlakukannya Pasal a quo. 4. Terkait adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa Para Pemohon merasa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal a quo dapat merugikan Para Pemohon yang pada Pemilu 2019 bertugas sebagai penyelenggara pemilu dengan menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan permasalahan yang disampaikan oleh para pemohon adalah pengalaman Para Pemohon dalam penyelenggaraan pemilu 2019 yang belum tentu terjadi atau dialami oleh Para Pemohon dalam setiap penyelenggaraan pemilu atau penyelenggaraan mendatang. Selain itu, Para Pemohon dalam permohonannya tidak dapat mengonstruksikan dengan jelas adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya Pasal a quo terhadap Para Pemohon. Oleh karenanya, dengan tidak adanya konstruksi kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon maka jelas tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan konstitusionalitas Pasal a quo. 5. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa dengan tidak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan ketentuan Pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian Pasal a quo tidak akan berdampak apa pun pada Para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi MK untuk memeriksa dan memutus permohonan Pasal a quo, karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga sudah sepatutnya MK tidak mempertimbangkan pokok perkara. Pokok permohonan: 1. Para Pemohon yang mendalilkan bahwa proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang mesti selesai di hari yang sama, dan dapat diperpanjang hingga pukul 12.00 pada hari berikutnya, sepanjang tidak ada jeda, membuat bobot tugas dan rasionalisasi beban kerja penyelenggara sangat ditentukan oleh jenis pemilihan yang dilaksanakan pada satu hari yang sama. (vide Perbaikan Permohonan halaman 17 angka 24). Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa perihal batas waktu tersebut sesungguhnya tidak ada lagi persoalan konstitusionalitas norma karena MK telah memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 (poin 3.17 angka 5) dengan menambahkan ketentuan perpanjangan waktu maksimal selama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN sepanjang penghitungan suara dilakukan secara tidak terputus (tanpa jeda waktu). MK juga berpendapat bahwa apabila tambahan waktu 12 jam tersebut diperpanjang lebih lama lagi maka akan menimbulkan permasalahan lain di tingkat KPPS, di samping itu pembatasan waktu hanya selama 12 jam juga untuk mengurangi segala kemungkinan risiko kecurangan. Berdasarkan hal tersebut, DPR berpandangan bahwa tidak ada jalan keluar lain apabila turut mempertimbangkan beban kerja yang dianggap berat oleh Para Pemohon, sebab jika diberikan waktu tambahan lebih lagi dari 12 jam tersebut maka akan menimbulkan permasalahan lain di tingkat KPPS. Bahwa perihal batas waktu penghitungan suara pada hari pemungutan suara, Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu menyatakan: Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara. Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu dalam hubungannya dengan permohonan a quo, sebagaimana telah disinggung di atas, adalah apakah batas waktu penghitungan suara yang harus selesai pada hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu berpotensi menyebabkan munculnya persoalan hukum yang dapat mengganggu keabsahan Pemilu, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dalam kaitan ini para Pemohon mendalilkan ihwal batas waktu penghitungan suara harus selesai pada hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu berpotensi tidak terpenuhi dalam penyelenggaraan pemilu serentak sehingga dapat menimbulkan masalah dan komplikasi hukum yang dapat menyebabkan dipersoalkannya keabsahan Pemilu 2019. Terhadap dalil tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama karena untuk pertama kalinya, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilu anggota legislatif (yaitu pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota). Salah satu konsekuensi keserentakan pemilu dimaksud adalah bertambahnya jenis surat dan kotak suara. Jika pada Pemilu 2014, in casu pemilu anggota legislatif, terdapat empat kotak suara maka pada Pemilu 2019, yang menggabungkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilu anggota legislatif, terdapat lima kotak suara. Penyelenggaraan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, akan menimbulkan beban tambahan dalam penyelenggaraan termasuk memerlukan waktu lebih lama. Apalagi, jumlah partai politik peserta Pemilu 2019 lebih banyak dari Pemilu 2014. Terkait dengan hal itu, Pasal 350 ayat (1) UU Pemilu mengantisipasi dengan cara membatasi bahwa pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Bahkan, setelah melalui simulasi, sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, KPU mengatur bahwa jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 orang. Bahwa sekalipun jumlah pemilih untuk setiap TPS telah ditetapkan paling banyak 300 orang, namun dengan banyaknya jumlah peserta pemilu, yang terdiri dari dua pasangan calon presiden, 16 (enam belas) partai politik nasional dan khusus Aceh ditambah dengan 4 (empat) partai politik lokal peserta pemilu dengan tiga tingkat pemilihan, dan perorangan calon anggota DPD, serta kompleksnya formulir-formulir yang harus diisi dalam penyelesaian proses penghitungan suara, potensi tidak selesainya proses penghitungan suara pada hari pemungutan suara sangat terbuka. Belum lagi jika faktor kapasitas dan kapabilitas aparat penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat TPS, turut dipertimbangkan. Oleh karena itu, dalam hal potensi yang tak dikehendaki tersebut benar-benar terjadi, sementara UU Pemilu menentukan pembatasan waktu yang sangat singkat dalam menghitung suara yang harus selesai pada hari pemungutan suara, maka keabsahan hasil pemilu akan menjadi terbuka untuk dipersoalkan. Bahwa untuk mengatasi potensi masalah tersebut maka ketentuan pembatasan waktu penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu harus dibuka namun dengan tetap memerhatikan potensi kecurangan yang mungkin terjadi. Potensi kecurangan mana akan terbuka jika proses penghitungan suara yang tidak selesai pada hari pemungutan suara lalu dilanjutkan pada hari berikutnya dengan disertai jeda waktu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, perpanjangan jangka waktu penghitungan suara hanya dapat dilakukan sepanjang proses penghitungan dilakukan secara tidak terputus hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN. Perpanjangan hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN, yaitu pukul 24.00 waktu setempat, merupakan waktu yang masuk akal, jika waktu tersebut diperpanjang lebih lama lagi justru akan dapat menimbulkan masalah lain di tingkat KPPS. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, sebagian dalil para Pemohon sepanjang menyangkut pembatasan waktu penghitungan suara di TPS/TPSLN sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu cukup beralasan. Hanya saja, untuk mengurangi segala kemungkinan risiko, terutama risiko kecurangan, lama perpanjangan waktu penghitungan suara cukup diberikan paling lama 12 (dua belas) jam. Dengan waktu tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikan potensi tidak selesainya proses penghitungan suara di TPS/TPSLN pada hari pemungutan suara. Sehubungan dengan itu, maka Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.” 2. Bahwa MK telah menyatakan pendiriannya mengenai lima pilihan model keserentakan pemilihan umum yang dijabarkan MK dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. MK juga menegaskan penentuan model pemilu serentak mana yang akan digunakan adalah wewenang DPR untuk memutuskannya. Hal ini sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukum MK sebagai berikut: Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum. (vide Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 pertimbangan hukum 3.16 paragraf 3) Oleh karena itu dalil-dalil Para Pemohon sudah seharusnya menjadi gugur dan tidak dipertimbangkan lagi oleh MK. 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 24/PUU-XVII/2019, MK pernah mengubah pendiriannya mengenai pandangan hukumnya terhadap pengujian norma undang-undang. Namun perubahan pendirian MK tersebut dilakukan dengan memperhatikan adanya suatu kejadian yang luar biasa sejak Putusan MK dibacakan. Selengkapnya pertimbangan hukum MK tersebut menyatakan: [3.18] Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan, misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi common law, yang sangat ketat menerapkan asas precedent atau stare decisis atau res judicata, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi. Tercatat misalnya, untuk menyebut beberapa contoh, bagaimana Mahkamah Agung Amerika Serikat yang semula berpendapat bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas warna kulit tidaklah bertentangan dengan Konstitusi sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip separate but equal (terpisah tetapi sama), sebagaimana diputus dalam kasus Plessy v. Fergusson (1896), kemudian berubah dengan menyatakan bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas dasar warna kulit adalah bertentangan dengan Konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam putusannya pada kasus Brown v. Board of Education (1954). Demikian pula ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat mengubah pendiriannya dalam permasalahan hak untuk didampingi penasihat hukum bagi seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam proses peradilan. Semula, dalam kasus Betts v. Brady (1942), Mahkamah Agung Amerika Serikat berpendirian bahwa penolakan pengadilan negara bagian untuk menyediakan penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Namun, melalui putusannya dalam kasus Gideon v. Wainwright (1963), Mahkamah Agung mengubah pendiriannya dan berpendapat sebaliknya, yaitu seseorang yang tidak mampu yang didakwa melakukan tindak pidana namun tanpa didampingi penasihat hukum adalah bertentangan dengan Konstitusi. Oleh karena itu, Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi civil law, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare decisis, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara. Bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon agar menguji kembali pasal yang telah diputus oleh MK. Bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. 4. DPR menerangkan bahwa MK tidak pernah membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, apabila norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka (open legal policy) sebagaimana MK tegaskan dalam pertimbangan hukum MK dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau Sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. 5. DPR menerangkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf g UU Pemilu adalah mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa orang-orang yang bertugas menjadi PPK, PPS dan KPPS adalah orang yang berkualifikasi sehat jasmani dan rohani. Persoalan banyaknya petugas PPK, PPS, dan KPPS yang sakit bahkan sampai meninggal karena beban kerja dalam pelaksanaan tugasnya bukanlah disebabkan ketentuan Pasal a quo maupun format pemilu serentak yang dimaksud UU Pemilu, melainkan karena kondisi orang yang ditugaskan sebagai PPK, PPS, dan KPPS dan tentunya hal tersebut bersifat kasuistis. Hal tersebut didukung hasil penelitian forensik verbal yang dilakukan Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Fakultas Kedokteran UGM, dan Fakultas Psikologi UGM yang menyimpulkan bahwa penyebab kematian PPS dalam Pemilu 2019 bahwa beban kerja yang berat memicu kelelahan, dampak lanjutan dari kelelahan tersebut adalah penyakit-penyakit para petugas muncul ke permukaan. Para peneliti berkeyakinan bahwa para petugas tersebut memang telah memiliki masalah kesehatan seperti diabetes dan jantung (vide https://www.voaindonesia.com/a/ mencari-penyebab-meninggalnya-petugas-pemilu/5294717.html). Oleh karena itu DPR berpandangan bahwa penyebab utama sakit dan meninggalnya petugas penyelenggara pemilu tersebut adalah karena faktor kesehatan karena penyakit bawaan dan bukan karena pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara serentak sebagaimana ketentuan Pasal a quo. 6. Bahwa Para Pemohon pernah mengujikan dalam Permohonan nomor 37/PUU-XVII/2009 dan Permohonan nomor 55/PUU-XVII/2019 berkaitan dengan norma keserentakan pemilu dan alasan-alasan yang disampaikan dalam permohonan pengujian a quo juga tidak didasarkan pada alasan-alasan konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelum permohonan a quo. Dengan demikian berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan Para Pemohon adalah ne bis in idem. 7. Terkait dengan penormaan baru yang dimohonkan oleh Para Pemohon kepada MK mengenai format keserentakan Pemilu (vide Perbaikan Permohonan Halaman 21 angka 45), DPR menerangkan bahwa hal tersebut merupakan ranah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yakni DPR dan Presiden sesuai Pasal 5 dan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945. Apabila Para Pemohon menginginkan adanya perubahan norma mengenai format keserentakan Pemilu sebagaimana diatur Pasal a quo, maka upaya yang seharusnya dilakukan adalah menyampaikan kepada DPR dan Pemerintah (Presiden) selaku pembentuk UU sebagai masukan untuk dilakukan perubahan atau penggantian terhadap ketentuan Pasal a quo maupun masukan terhadap pelaksanaan pemilu serentak yang lebih baik ke depannya. 8. Bahwa terhadap permohonan provisi yang diajukan Para Pemohon, DPR menerangkan bahwa pada awalnya MK tidak mengenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, namun pada perkembangan selanjutnya MK mengenal putusan provisi yang menyangkut pemeriksaan prioritas agar perkara yang diajukan segera dapat diputus. Perkara-perkara yang dikabulkan pemeriksaannya secara cepat adalah pengujian undang-undang terkait pemilu dan pilkada sebagaimana ditemukan dalam 4 (empat) putusan, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XVII/2019. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon karena terdapat alasan yang kuat untuk itu, permohonan provisi dalam pengujian undang-undang akan dipertimbangkan secara tersendiri dan secara kasuistis yang menurut pendapat MK relevan dan mendesak untuk dilakukan. Namun, dalam perkara a quo DPR memandang tidak ada alasan yang kuat bahwa ada hal yang mendesak untuk dikabulkannya permohonan provisi Para Pemohon a quo. Oleh karena itu, sudah selayaknya MK menolak permohonan provisi para Pemohon.
16/PUU-XIX/2021
Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu
Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945